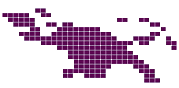Masyarakat Adat Independen (MAI) Desak Pemerintah Tutup Operasional Tambang PTFI
pada tanggal
Sunday, 2 April 2017
JAKARTA- Masyarakat adat yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) mendesak pemerintah menutup operasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Alasannya, masyarakat adat dua suku besar yakni Suku Amungme dan Suku Kamoro mengklaim telah menjadi korban kompromi pemerintah dan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu selama 50 tahun.
Sekretaris MAI sekaligus Perwakilan dari Suku Kamoro, Ronny Nakiaya mengungkapkan, ada empat tuntutan MAI kepada pemerintah Indonesia. Pertama, tutup Freeport. Kedua, segera audit hasil kekayaan Freeport dan mewajibkan membayar upah atau pesangon pekerja sesuai ketentuan berlaku.
"Kami minta tutup Freeport dulu, baru audit kekayaan Freeport. Jangan-jangan yang dibawa keluar lebih banyak, sementara dana tanggungjawab sosial (CSR) cuma 1 persen, apakah itu sesuai," tegas Ronny saat Konferensi Pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (2/4/2017).
Pasca audit dari lembaga independen, diharapkan Ronny, ada perundingan tripatrit antara Freeport Indonesia, pemerintah, serta masyarakat adat Papua. Inilah yang ditunggu-tunggu selama 50 tahun oleh masyarakat adat, sehingga hak-hak mereka dihargai.
Tuntutan ketiga, Freeport dan pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab mengembalikan kerugian alam yang sudah dirusak. Terakhir, membiarkan masyarakat yang menentukan masa depan pertambangan di Tanah Papua.
"Sebab Freeport harus bertanggungjawab pada lingkungan di dekat daerah operasi yang sudah rusak, tanggul bocor, sekitar ratusan hektare (ha) tanah tandus, gunung-gunung bolong karena dikeruk. Itu kerugian sudah berapa? Ini yang harus dikembalikan Freeport," Ronny menuntut.
Empat tuntutan tersebut diakui Ronny, sudah disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini ke Kantor Staf Presiden (KSP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Tapi belum ada respons dari KSP dan Kementerian ESDM. Tapi kami akan terus berjuang, dan meminta masyarakat Indonesia mendukung langkah kami karena selama ini masyarakat adat menjadi korban kepentingan Freeport dan pemerintah," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pemuda di MAI sekaligus perwakilan dari Suku Kamoro, Nicolaus Kanunggok menegaskan, masyarakat adat tidak meminta selembar saham pun apabila pemerintah pusat memberikan 5 persen saham Freeport kepada pemerintah daerah. Yang dibutuhkan hanyalah kepastian.
"Pada dasarnya kami meminta pemerintah tutup Freeport Indonesia, audit segera karena situasi konflik yang sudah terjadi bikin bingung. Kami tidak minta berapa persen. Tutup, lalu audit, dan mereka ambil berapa, dan biarkan masyarakat adat yang menentukan," ucapnya.
Jadi Korban Freeport
Tuntutan tersebut sebelumnya lahir karena masyarakat adat Amungme dan Kamoro merasa hak-haknya selama ini diabaikan pemerintah dan Freeport Indonesia. Hal tersebut bermula dari semenjak masuk di Timika, Papua pada 1967 melalui legalitas Undang-undang Penanaman Modal Asing, Freeport dan pemerintah Indonesia tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat dua suku besar di Bumi Papua, Amungme dan Komoro dalam setiap proses negosiasi.
"Hak tanah adat dirampas Freeport tanpa negosiasi dengan masyarakat adat. Hak-hak sipil, sehingga timbul konflik kepentingan elit di masyarakat, masyarakat di adu domba," kata Ronny.
Belum lagi hak-hak lingkungan yang sudah rusak dari kegiatan penambangan Freeport. Menurutnya, masyarakat setempat kini kehilangan mata pencaharian karena yang biasanya bertani atau meramu makanan sendiri, sudah tidak dapat melakukannya lantaran terkena limbah dari aktivitas penambangan.
"Dari sisi kekerasan, kami tidak bisa masuk ke area-area Freeport tanpa izin tertentu, padahal itu dianggap tanah leluhur mereka," paparnya.
Ronny menegaskan, selama hadir di Indonesia sejak 1967 lalu, Freeport tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada rakyat Papua, termasuk masyarakat adat dua suku tersebut. Sampai akhirnya pada 1996, sambungnya, muncul perlawanan yang menelan korban jiwa. Saat itulah, ruang-ruang tertutup itu perlahan terbuka.
"Sejak 1967 Freeport beroperasi, tidak ada kontribusinya. Barulah pada 1996, mereka memberikan dana bantuan yang dibalut dengan program tanggungjawab sosial (CSR) sebesar 1 persen untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Freeport sejak masuk Timika," paparnya.
Sayangnya, dia bilang, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu tidak transparan dengan penyaluran dana tersebut, termasuk dengan jumlahnya. Ronny mengaku, dana CSR 1 persen dari Freeport tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tapi hanya menimbulkan konflik internal di kalangan masyarakat akar rumput dan elit.
"Dana CSR kan harusnya lari ke masyarakat, tapi ini malah yang dapat pemerintah, militer. Lalu buat kami dapat apa. Transparansi tidak jelas berapa dananya. Kami tidak pernah tahu data apapun dari mereka, karena mereka menutup rapat semua informasi ke luar," tegas Ronny. (liputan6)
Sekretaris MAI sekaligus Perwakilan dari Suku Kamoro, Ronny Nakiaya mengungkapkan, ada empat tuntutan MAI kepada pemerintah Indonesia. Pertama, tutup Freeport. Kedua, segera audit hasil kekayaan Freeport dan mewajibkan membayar upah atau pesangon pekerja sesuai ketentuan berlaku.
"Kami minta tutup Freeport dulu, baru audit kekayaan Freeport. Jangan-jangan yang dibawa keluar lebih banyak, sementara dana tanggungjawab sosial (CSR) cuma 1 persen, apakah itu sesuai," tegas Ronny saat Konferensi Pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (2/4/2017).
Baca Juga
Pasca audit dari lembaga independen, diharapkan Ronny, ada perundingan tripatrit antara Freeport Indonesia, pemerintah, serta masyarakat adat Papua. Inilah yang ditunggu-tunggu selama 50 tahun oleh masyarakat adat, sehingga hak-hak mereka dihargai.
Tuntutan ketiga, Freeport dan pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab mengembalikan kerugian alam yang sudah dirusak. Terakhir, membiarkan masyarakat yang menentukan masa depan pertambangan di Tanah Papua.
"Sebab Freeport harus bertanggungjawab pada lingkungan di dekat daerah operasi yang sudah rusak, tanggul bocor, sekitar ratusan hektare (ha) tanah tandus, gunung-gunung bolong karena dikeruk. Itu kerugian sudah berapa? Ini yang harus dikembalikan Freeport," Ronny menuntut.
Empat tuntutan tersebut diakui Ronny, sudah disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini ke Kantor Staf Presiden (KSP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Tapi belum ada respons dari KSP dan Kementerian ESDM. Tapi kami akan terus berjuang, dan meminta masyarakat Indonesia mendukung langkah kami karena selama ini masyarakat adat menjadi korban kepentingan Freeport dan pemerintah," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pemuda di MAI sekaligus perwakilan dari Suku Kamoro, Nicolaus Kanunggok menegaskan, masyarakat adat tidak meminta selembar saham pun apabila pemerintah pusat memberikan 5 persen saham Freeport kepada pemerintah daerah. Yang dibutuhkan hanyalah kepastian.
"Pada dasarnya kami meminta pemerintah tutup Freeport Indonesia, audit segera karena situasi konflik yang sudah terjadi bikin bingung. Kami tidak minta berapa persen. Tutup, lalu audit, dan mereka ambil berapa, dan biarkan masyarakat adat yang menentukan," ucapnya.
Jadi Korban Freeport
Tuntutan tersebut sebelumnya lahir karena masyarakat adat Amungme dan Kamoro merasa hak-haknya selama ini diabaikan pemerintah dan Freeport Indonesia. Hal tersebut bermula dari semenjak masuk di Timika, Papua pada 1967 melalui legalitas Undang-undang Penanaman Modal Asing, Freeport dan pemerintah Indonesia tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat dua suku besar di Bumi Papua, Amungme dan Komoro dalam setiap proses negosiasi.
"Hak tanah adat dirampas Freeport tanpa negosiasi dengan masyarakat adat. Hak-hak sipil, sehingga timbul konflik kepentingan elit di masyarakat, masyarakat di adu domba," kata Ronny.
Belum lagi hak-hak lingkungan yang sudah rusak dari kegiatan penambangan Freeport. Menurutnya, masyarakat setempat kini kehilangan mata pencaharian karena yang biasanya bertani atau meramu makanan sendiri, sudah tidak dapat melakukannya lantaran terkena limbah dari aktivitas penambangan.
"Dari sisi kekerasan, kami tidak bisa masuk ke area-area Freeport tanpa izin tertentu, padahal itu dianggap tanah leluhur mereka," paparnya.
Ronny menegaskan, selama hadir di Indonesia sejak 1967 lalu, Freeport tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada rakyat Papua, termasuk masyarakat adat dua suku tersebut. Sampai akhirnya pada 1996, sambungnya, muncul perlawanan yang menelan korban jiwa. Saat itulah, ruang-ruang tertutup itu perlahan terbuka.
"Sejak 1967 Freeport beroperasi, tidak ada kontribusinya. Barulah pada 1996, mereka memberikan dana bantuan yang dibalut dengan program tanggungjawab sosial (CSR) sebesar 1 persen untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Freeport sejak masuk Timika," paparnya.
Sayangnya, dia bilang, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu tidak transparan dengan penyaluran dana tersebut, termasuk dengan jumlahnya. Ronny mengaku, dana CSR 1 persen dari Freeport tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tapi hanya menimbulkan konflik internal di kalangan masyarakat akar rumput dan elit.
"Dana CSR kan harusnya lari ke masyarakat, tapi ini malah yang dapat pemerintah, militer. Lalu buat kami dapat apa. Transparansi tidak jelas berapa dananya. Kami tidak pernah tahu data apapun dari mereka, karena mereka menutup rapat semua informasi ke luar," tegas Ronny. (liputan6)