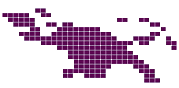Fakfak, Bukti Keharmonisan Beragama Negeri Tiga Tungku
pada tanggal
Saturday, 31 October 2015
AMBON - Kericuhan atas nama agama serta upaya meruncungkan sentimen agama di Indonesia, pasca terbakarnya masjid di Tolikara membuat wilayah Indonesia lain berjaga-jaga. Mereka menganggap penyebab kericuhan itu murni politisasi semata. Namun yang paling dikhawatirkan adalah pemberitaan provokatif yang berusaha mengaburkan fakta sebenarnya keharmonisan antar umat beragama di Papua.
:Salamualaikum". Demikian salam spontan dari Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Fakfak, Kabupaten Fakfak, Falentinus Kabes ketika menjawab telepon saya. Padahal, pria yang akrab dipanggil Falen tersebut adalah seorang Nasrani. Sebuah sapaan yang mengesankan toleransi.
Dia memang saya telepon terkait dengan meletusnya konflik Tolikara. Saya meminta pandangan dia tentang konflik tersebut dan bagaimana imbasnya ke Fakfak. Sebab, Fakfak adalah kabupaten dengan populasi muslim terbanyak di Papua. Di antara total 100 ribuan warga, lebih dari 80 persen adalah muslim.
Namun, warga Fakfak sangat dewasa. Mereka justru sudah saling berkomunikasi. “Kami sudah saling menjaga. Salat Id dan tradisi Lebaran muslim di sini justru dijaga orang Nasrani. Begitu pula misa. Nanti dan besok giliran misa yang dijaga saudara kami yang muslim,” jelas Kabes.
Mekanisme satu tungku tiga batu kembali berjalan. Satu tungku tiga batu adalah sebuah konsep yang dianut masyarakat Fakfak. Di Jazirah Fakfak, ada tujuh petuanan (semacam kerajaan) yang masih diturut masyarakat. Yakni, Petuanan Ati-Ati, Petuanan Fatagar, Petuanan Piq-Piq, Petuanan Arguni, Petuanan Teluk Patipi, Petuanan Wertuer, dan Petuanan Rumbati.
Sistem adat tersebut berkolaborasi dengan tiga agama yang dianut masyarakat. Yakni, Islam, Kristen, serta Katolik. Para petuanan itu berkolaborasi dengan sistem agama dengan cara yang khas Papua. Yaitu, jika ada satu marga/petuanan yang anggota keluarganya “terlalu banyak” yang muslim, para tetuanya kemudian menyuruh salah seorang anggota keluarga untuk memeluk Kristen atau Katolik. Begitu pula sebaliknya. Jika terlalu banyak yang Nasrani, sebagian disuruh masuk Islam.
Sebagaimana yang dimuat dalam Jelajah Semenanjung Raja-Raja, sistem itulah yang membentuk kerukunan umat beragama di Fakfak.
“Di Fakfak tidak ada masalah. Aman sudah,” tegas Kabes.
Dalam edisi yang sama disebutkan pula, seorang Nasrani Fakfak bahkan mempunyai dua alat masak dan piring. Yang satu untuk sehari-hari dan satu lagi khusus untuk menjamu saudara mereka yang muslim. Hal itu ditujukan untuk melindungi tamu agar tetap menyantap makanan dari piring dan gelas yang tidak pernah dipakai menghidangkan masakan yang tidak halal.
Namun, Kabes menegaskan, yang membuat pusing adalah pemberitaan di media-media. “Kami sempat dengar, katanya ada muslim Jawa yang mau ke sini. Ngapain? Malah hanya memperkeruh suasana. Bisa dianggap tantangan. Biar diselesaikan di sini sudah. Kalau dari luar ikut-ikut, bisa tidak selesai itu dorang pe perkara,” tegasnya dengan sedikit dialek Papua.
Untuk sementara, di Kaimana dan Bintuni, situasi harmonis seperti di Fakfak juga terjadi. Mereka juga menganut ideologi yang sama, yakni satu tungku tiga batu.
Hal yang sama terjadi di Raja Ampat. Meski tidak mengenal prinsip satu tungku tiga batu seperti di Fakfak, masyarakat Raja Ampat mempunyai tingkat kerukunan beragama yang tidak kalah akrab.
“Di sini memang biasa jika ada satu keluarga yang campur-campur. Tidak hanya di Raja Ampat, tetapi hampir di semua tempat di Papua,” tutur Imam Masjid Agung Waisai Raja Ampat H M. Hanafing.
Menurut dia, begitu mendengar konflik Tolikara meletus, dirinya melakukan sejumlah antisipasi. Antara lain, memberikan sosialisasi kepada umatnya dan pemuka agama lain. Tetapi, itu dilakukan masih secara informal. “Masih banyak yang belum tahu. Kecuali pengakses internet. Karena itu, saya tidak gegabah untuk memberikan sosialisasi menyeluruh,” ucapnya.
Hanafing mengungkapkan, pihaknya baru akan memberikan sosialisasi menyeluruh kepada umat jika informasi sudah tersebar luas. “Jelas, saya akan imbau jamaah untuk memahami bahwa ini bukan konflik agama. Kalau saya lihat, kecenderungannya politis. Lagi pula, kalaupun ini memang konflik agama, kedatangan orang luar justru membuat makin rumit,” tambahnya.
Hanya, Hanafing menyesalkan pemberitaan di sejumlah media online yang isinya dianggap sangat memanas-manasi. “Misalnya, mempertanyakan bagaimana sikap umat muslim, ajakan jihad, atau komentar menyerang gereja. Menurut saya, jika terus-menerus dicekoki seperti ini, siapa pun bisa dengan gampang tersulut emosinya. Susah bagi kami untuk menahannya,” tegasnya.
Toleransi Kehidupan
Di kawasan Indonesia Timur sebenarnya ada sebuah kelenturan antarumat beragama. Baik di kawasan Maluku (Ambon dan sekitarnya), Maluku Utara (Ternate, Tidore, dan Bacan), maupun Papua.
Dari perjalanan Jelajah Semenanjung Raja-Raja (menyeberangi sembilan pulau dan 15 titik) di kawasan Indonesia Timur, saya melihat sendiri praktik-praktik toleransi dan kerukunan umat beragama itu. Di Papua serta Maluku yang sering secara serampangan disebut “pusat Kristen”, ada sebuah sikap adat yang membuat setiap pemeluk agama boleh menjalankan keyakinan mereka.
Salam “assalamualaikum” dari orang Nasrani kepada muslim bukan hal yang aneh. Bahkan, di beberapa kampung di Maluku, seseorang tidak akan tahu dirinya masuk kampung Kristen. Sebab, warganya berpeci dan berkopiah. Mereka pun sangat toleran. Salah satu contohnya ketika bulan puasa lalu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang makan, minum, atau merokok ketika tahu saya adalah muslim. Mereka juga tidak akan merokok ketika masuk ke kampung muslim.
Yang paling radikal, misalnya, “membagi-bagi” anggota keluarga untuk memeluk Islam atau Kristen. Atau, ikut duduk mengikuti misa Natal dan khotbah Idul Fitri. Seorang Nasrani menjadi ketua panitia pembangunan masjid adalah hal biasa di Indonesia Timur, khususnya Papua.
Memang sulit dipercaya. Tetapi, itu betul-betul saya temui dan saya lihat sendiri selama liputan sepanjang Ramadan lalu.
Coba bandingkan dengan di Jawa. Jangankan untuk mengucapkan selamat Natal, wacana Islam Nusantara saja sudah menjadi kontroversi hebat. Dalam konteks toleransi dan kerukunan umat beragama, Jawa jauh tertinggal dari Indonesia Timur.
Karena itu, ketika krisis tersebut meletus di sebuah kota terpencil di Papua, lalu menjadi berita utama banyak media, banyak warga Papua yang marah. Sebab, mereka merasa seolah menjadi suku barbar yang tidak beradab dan suka menyerang saat saudaranya salat.
Pertanyaannya, dengan tingkat toleransi masyarakat yang menganggap agama adalah persaudaraan, mengapa masih terjadi konflik seperti di Tolikara? Selalu ada dua penyebab dalam tiap konflik. Salah satunya adalah faktor eksternal. Yakni, konflik didesain oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu memang sudah terlihat dari sejumlah konflik besar di Indonesia Timur sejak 1999.
Namun, tentu tidak bisa menyalakan api di jerami yang basah. Meski mempunyai tingkat toleransi beragama yang besar, tetap saja susunan sosial masyarakat di Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, masih rapuh. Bukti paling nyata, selalu ada pemuda-pemuda -yang nyaris tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan- yang berkumpul, minum minuman keras, dan lantas melakukan hal-hal yang kerap tidak baik.
Perkelahian antar pemuda, antarkampung, atau antarsuku kerap terjadi karena para pemuda. Itu pun disebabkan masalah yang sangat sepele. Misalnya, senggolan di pentas musik atau hanya karena saling pandang. Selain itu, para pemuda tersebut umumnya masih menganggap dirinya anak adat sehingga mudah diprovokasi untuk melakukan sesuatu.
Jangan hanya karena Tolikara lantas semua orang Papua dianggap barbar dan tidak punya empati beragama. Papua sangat luas. Jika disamakan dengan di Jawa, skala Tolikara mungkin setingkat kecamatan di kabupaten paling terpencil.
“Kami memang masih mempunyai masalah sosial. Tetapi, jangan seret kami seperti yang terjadi di Ambon,” tegas Achmad Hindom, Warnemen (wakil ketua kampung) dari Petuaan Fatagar. [AmbonExpress]
:Salamualaikum". Demikian salam spontan dari Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Fakfak, Kabupaten Fakfak, Falentinus Kabes ketika menjawab telepon saya. Padahal, pria yang akrab dipanggil Falen tersebut adalah seorang Nasrani. Sebuah sapaan yang mengesankan toleransi.
Dia memang saya telepon terkait dengan meletusnya konflik Tolikara. Saya meminta pandangan dia tentang konflik tersebut dan bagaimana imbasnya ke Fakfak. Sebab, Fakfak adalah kabupaten dengan populasi muslim terbanyak di Papua. Di antara total 100 ribuan warga, lebih dari 80 persen adalah muslim.
Baca Juga
Namun, warga Fakfak sangat dewasa. Mereka justru sudah saling berkomunikasi. “Kami sudah saling menjaga. Salat Id dan tradisi Lebaran muslim di sini justru dijaga orang Nasrani. Begitu pula misa. Nanti dan besok giliran misa yang dijaga saudara kami yang muslim,” jelas Kabes.
Mekanisme satu tungku tiga batu kembali berjalan. Satu tungku tiga batu adalah sebuah konsep yang dianut masyarakat Fakfak. Di Jazirah Fakfak, ada tujuh petuanan (semacam kerajaan) yang masih diturut masyarakat. Yakni, Petuanan Ati-Ati, Petuanan Fatagar, Petuanan Piq-Piq, Petuanan Arguni, Petuanan Teluk Patipi, Petuanan Wertuer, dan Petuanan Rumbati.
Sistem adat tersebut berkolaborasi dengan tiga agama yang dianut masyarakat. Yakni, Islam, Kristen, serta Katolik. Para petuanan itu berkolaborasi dengan sistem agama dengan cara yang khas Papua. Yaitu, jika ada satu marga/petuanan yang anggota keluarganya “terlalu banyak” yang muslim, para tetuanya kemudian menyuruh salah seorang anggota keluarga untuk memeluk Kristen atau Katolik. Begitu pula sebaliknya. Jika terlalu banyak yang Nasrani, sebagian disuruh masuk Islam.
Sebagaimana yang dimuat dalam Jelajah Semenanjung Raja-Raja, sistem itulah yang membentuk kerukunan umat beragama di Fakfak.
“Di Fakfak tidak ada masalah. Aman sudah,” tegas Kabes.
Dalam edisi yang sama disebutkan pula, seorang Nasrani Fakfak bahkan mempunyai dua alat masak dan piring. Yang satu untuk sehari-hari dan satu lagi khusus untuk menjamu saudara mereka yang muslim. Hal itu ditujukan untuk melindungi tamu agar tetap menyantap makanan dari piring dan gelas yang tidak pernah dipakai menghidangkan masakan yang tidak halal.
Namun, Kabes menegaskan, yang membuat pusing adalah pemberitaan di media-media. “Kami sempat dengar, katanya ada muslim Jawa yang mau ke sini. Ngapain? Malah hanya memperkeruh suasana. Bisa dianggap tantangan. Biar diselesaikan di sini sudah. Kalau dari luar ikut-ikut, bisa tidak selesai itu dorang pe perkara,” tegasnya dengan sedikit dialek Papua.
Untuk sementara, di Kaimana dan Bintuni, situasi harmonis seperti di Fakfak juga terjadi. Mereka juga menganut ideologi yang sama, yakni satu tungku tiga batu.
Hal yang sama terjadi di Raja Ampat. Meski tidak mengenal prinsip satu tungku tiga batu seperti di Fakfak, masyarakat Raja Ampat mempunyai tingkat kerukunan beragama yang tidak kalah akrab.
“Di sini memang biasa jika ada satu keluarga yang campur-campur. Tidak hanya di Raja Ampat, tetapi hampir di semua tempat di Papua,” tutur Imam Masjid Agung Waisai Raja Ampat H M. Hanafing.
Menurut dia, begitu mendengar konflik Tolikara meletus, dirinya melakukan sejumlah antisipasi. Antara lain, memberikan sosialisasi kepada umatnya dan pemuka agama lain. Tetapi, itu dilakukan masih secara informal. “Masih banyak yang belum tahu. Kecuali pengakses internet. Karena itu, saya tidak gegabah untuk memberikan sosialisasi menyeluruh,” ucapnya.
Hanafing mengungkapkan, pihaknya baru akan memberikan sosialisasi menyeluruh kepada umat jika informasi sudah tersebar luas. “Jelas, saya akan imbau jamaah untuk memahami bahwa ini bukan konflik agama. Kalau saya lihat, kecenderungannya politis. Lagi pula, kalaupun ini memang konflik agama, kedatangan orang luar justru membuat makin rumit,” tambahnya.
Hanya, Hanafing menyesalkan pemberitaan di sejumlah media online yang isinya dianggap sangat memanas-manasi. “Misalnya, mempertanyakan bagaimana sikap umat muslim, ajakan jihad, atau komentar menyerang gereja. Menurut saya, jika terus-menerus dicekoki seperti ini, siapa pun bisa dengan gampang tersulut emosinya. Susah bagi kami untuk menahannya,” tegasnya.
Toleransi Kehidupan
Di kawasan Indonesia Timur sebenarnya ada sebuah kelenturan antarumat beragama. Baik di kawasan Maluku (Ambon dan sekitarnya), Maluku Utara (Ternate, Tidore, dan Bacan), maupun Papua.
Dari perjalanan Jelajah Semenanjung Raja-Raja (menyeberangi sembilan pulau dan 15 titik) di kawasan Indonesia Timur, saya melihat sendiri praktik-praktik toleransi dan kerukunan umat beragama itu. Di Papua serta Maluku yang sering secara serampangan disebut “pusat Kristen”, ada sebuah sikap adat yang membuat setiap pemeluk agama boleh menjalankan keyakinan mereka.
Salam “assalamualaikum” dari orang Nasrani kepada muslim bukan hal yang aneh. Bahkan, di beberapa kampung di Maluku, seseorang tidak akan tahu dirinya masuk kampung Kristen. Sebab, warganya berpeci dan berkopiah. Mereka pun sangat toleran. Salah satu contohnya ketika bulan puasa lalu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang makan, minum, atau merokok ketika tahu saya adalah muslim. Mereka juga tidak akan merokok ketika masuk ke kampung muslim.
Yang paling radikal, misalnya, “membagi-bagi” anggota keluarga untuk memeluk Islam atau Kristen. Atau, ikut duduk mengikuti misa Natal dan khotbah Idul Fitri. Seorang Nasrani menjadi ketua panitia pembangunan masjid adalah hal biasa di Indonesia Timur, khususnya Papua.
Memang sulit dipercaya. Tetapi, itu betul-betul saya temui dan saya lihat sendiri selama liputan sepanjang Ramadan lalu.
Coba bandingkan dengan di Jawa. Jangankan untuk mengucapkan selamat Natal, wacana Islam Nusantara saja sudah menjadi kontroversi hebat. Dalam konteks toleransi dan kerukunan umat beragama, Jawa jauh tertinggal dari Indonesia Timur.
Karena itu, ketika krisis tersebut meletus di sebuah kota terpencil di Papua, lalu menjadi berita utama banyak media, banyak warga Papua yang marah. Sebab, mereka merasa seolah menjadi suku barbar yang tidak beradab dan suka menyerang saat saudaranya salat.
Pertanyaannya, dengan tingkat toleransi masyarakat yang menganggap agama adalah persaudaraan, mengapa masih terjadi konflik seperti di Tolikara? Selalu ada dua penyebab dalam tiap konflik. Salah satunya adalah faktor eksternal. Yakni, konflik didesain oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu memang sudah terlihat dari sejumlah konflik besar di Indonesia Timur sejak 1999.
Namun, tentu tidak bisa menyalakan api di jerami yang basah. Meski mempunyai tingkat toleransi beragama yang besar, tetap saja susunan sosial masyarakat di Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, masih rapuh. Bukti paling nyata, selalu ada pemuda-pemuda -yang nyaris tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan- yang berkumpul, minum minuman keras, dan lantas melakukan hal-hal yang kerap tidak baik.
Perkelahian antar pemuda, antarkampung, atau antarsuku kerap terjadi karena para pemuda. Itu pun disebabkan masalah yang sangat sepele. Misalnya, senggolan di pentas musik atau hanya karena saling pandang. Selain itu, para pemuda tersebut umumnya masih menganggap dirinya anak adat sehingga mudah diprovokasi untuk melakukan sesuatu.
Jangan hanya karena Tolikara lantas semua orang Papua dianggap barbar dan tidak punya empati beragama. Papua sangat luas. Jika disamakan dengan di Jawa, skala Tolikara mungkin setingkat kecamatan di kabupaten paling terpencil.
“Kami memang masih mempunyai masalah sosial. Tetapi, jangan seret kami seperti yang terjadi di Ambon,” tegas Achmad Hindom, Warnemen (wakil ketua kampung) dari Petuaan Fatagar. [AmbonExpress]