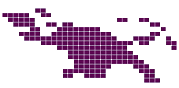Kemendagri akan Batalkan Ratusan Perda Diskriminatif
pada tanggal
Wednesday, 22 July 2015
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengecek kembali sejumlah peraturan daerah (perda) yang cenderung diskriminatif.
Adanya dugaan perda tentang tata cara beribadah yang melarang penggunaan alat pengeras suara saat ibadah berlangsung di Kabupaten Tolikara, juga tak luput dari pantauan Kemdagri.
"Perda-perda akan kami cek ulang," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (20/7).
Dia menegaskan, sejak dirinya menjabat sebagai mendagri, tidak pernah ada perda di Tolikara yang mengatur tata cara beribadah.
Dalam beberapa kesempatan, Tjahjo pernah menyatakan pihaknya bakal membatalkan sebuah perda jika diketahui bertentangan dengan Pancasila.
"Saya sudah mengembalikan 139 perda. Perda yang isinya tidak melihat negara ini adalah negara sebagai negara majemuk," tegasnya.
Dia menjelaskan, pembatalkan perda dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang diskriminatif. Dia berharap pembatalan itu membuat pemerintah daerah (pemda) lebih teliti menyusun perda.
"Perda yang baik tentu akan tingkatkan pembangunan. Kerukunan juga tercipta sehingga tidak terjadi konflik,” jelas mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
328 Perda Diskriminatif
Sebelumnya Direktur Pendidikan dan Penelitian Institut Perempuan dan Anak Indonesia Neng Dara Affiah mengatakan sebanyak 328 Perda yang dibuat masing-masing kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia ternyata bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan kaum minoritas.
Ia mengatakan pada 2008, tercatat sebanyak 172 Perda ternyata mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan dan kaum minoritas berdasarkan agama dan suku.
Kini, tuturnya, angka ini meningkat menjadi 328 Perda diskriminatif. Hal ini, dinilainya sangat ironis saat era keterbukaan dan sistem politik demokrasi diberlakukan dengan munculnya pasal khusus tentang Hak Asasi Manusia.
“Sekarang, Perda diskriminatif ada 328. Tahun 2008 memang ada 172 Perda. Setelah pemutakhiran data, ternyata bertambah. Ini ironis saat politik demokrasi dan era keterbukaan berlaku,” ujarnya dalam acara diskusi tentang Hak Azasi Perempuan di Yayasan Obor, Jakarta, Rabu (29/4).
Film berjudul Atas Nama menjadi bukti bagaimana perempuan dan kaum minoritas tak mendapat kesetaraan serta dihambat aksesnya untuk mendapat berbagai fasilitas.
Dalam film tersebut diceritakan bagaimana beberapa daerah justru mengekang ruang gerak perempuan melalui produk hukum. Aturan menutup aurat yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Aceh dengan terbitnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dirasa tak terlalu mendesak dibuat saat masalah kemiskinan justru dikesampingkan.
Daerah lainnya, seperti Kota Tangerang, Banten yang menjunjung nilai keislaman pun menorehkan cerita menyedihkan dengan lahirnya Perda Nomor 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran.
Lilis Lisdawati, seorang perempuan yang menjadi korban salah tangkap razia pekerja seks komersial (PSK) meninggal dunia pada 2008 dalam kondisi depresi berat. Lilis, saat itu keluar di malam hari. Lilis yang keluar seorang diri mengenakan celana panjang dan jaket justru diciduk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena dianggap sedang menjajakan diri.
Padahal, kala itu, Lilis sedang menunggu angkutan umum. Akibat kejadian itu, Lilis harus meringkuk di balik jeruji dan Pemerintah Kota Tangerang membuka secara umum sidang perkaranya di pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, Lilis dan suaminya harus keluar dari tempat kerjanya dan berpindah tempat tinggal karena mendapat stigma buruk dari masyarakat.
Cerita lainnya, sejak 2008 jemaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat yang harus hidup tanpa akses pendidikan dan tak diperbolehkan berdagang hanya karena dinilai menodai nilai agama Islam. Padahal, Ahmadiyah telah ada 1930 dan berbadan hukum sejak 1950. Akibatnya, penyerangan yang terjadi menggusur jemaah Ahmadiyah yang sejak lama menjadi pedagang dan menguasai pasar setempat.
Dia menilai saat masalah kemiskinan dan korupsi belum terurai, Pemerintah Daerah yang seharusnya bisa menjadi penyambung tangan Pemerintah Pusat ternyata belum dapat menunjukkan perannya. Perebutan kekuasaan atas nama identitas pun terjadi mulai dari daerah.
“Perebutannya justru di daerah. Politik identitas terjadi di tingkat daerah. Banyak kemunafikan. Hipokritas atas nama gender, agama atau suku. Perda pelacuran dan penggunaan jilbab dibuat. Padahal, korupsi tinggi sekali di Banten. Intoleransi berujung pada penyerangan kelompok minoritas dan korbannya perempuan dan anak,” katanya. [Antara/Bisnis]
Adanya dugaan perda tentang tata cara beribadah yang melarang penggunaan alat pengeras suara saat ibadah berlangsung di Kabupaten Tolikara, juga tak luput dari pantauan Kemdagri.
"Perda-perda akan kami cek ulang," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (20/7).
Dia menegaskan, sejak dirinya menjabat sebagai mendagri, tidak pernah ada perda di Tolikara yang mengatur tata cara beribadah.
Dalam beberapa kesempatan, Tjahjo pernah menyatakan pihaknya bakal membatalkan sebuah perda jika diketahui bertentangan dengan Pancasila.
"Saya sudah mengembalikan 139 perda. Perda yang isinya tidak melihat negara ini adalah negara sebagai negara majemuk," tegasnya.
Dia menjelaskan, pembatalkan perda dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang diskriminatif. Dia berharap pembatalan itu membuat pemerintah daerah (pemda) lebih teliti menyusun perda.
"Perda yang baik tentu akan tingkatkan pembangunan. Kerukunan juga tercipta sehingga tidak terjadi konflik,” jelas mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
328 Perda Diskriminatif
Sebelumnya Direktur Pendidikan dan Penelitian Institut Perempuan dan Anak Indonesia Neng Dara Affiah mengatakan sebanyak 328 Perda yang dibuat masing-masing kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia ternyata bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan kaum minoritas.
Ia mengatakan pada 2008, tercatat sebanyak 172 Perda ternyata mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan dan kaum minoritas berdasarkan agama dan suku.
Kini, tuturnya, angka ini meningkat menjadi 328 Perda diskriminatif. Hal ini, dinilainya sangat ironis saat era keterbukaan dan sistem politik demokrasi diberlakukan dengan munculnya pasal khusus tentang Hak Asasi Manusia.
“Sekarang, Perda diskriminatif ada 328. Tahun 2008 memang ada 172 Perda. Setelah pemutakhiran data, ternyata bertambah. Ini ironis saat politik demokrasi dan era keterbukaan berlaku,” ujarnya dalam acara diskusi tentang Hak Azasi Perempuan di Yayasan Obor, Jakarta, Rabu (29/4).
Film berjudul Atas Nama menjadi bukti bagaimana perempuan dan kaum minoritas tak mendapat kesetaraan serta dihambat aksesnya untuk mendapat berbagai fasilitas.
Dalam film tersebut diceritakan bagaimana beberapa daerah justru mengekang ruang gerak perempuan melalui produk hukum. Aturan menutup aurat yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Aceh dengan terbitnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dirasa tak terlalu mendesak dibuat saat masalah kemiskinan justru dikesampingkan.
Daerah lainnya, seperti Kota Tangerang, Banten yang menjunjung nilai keislaman pun menorehkan cerita menyedihkan dengan lahirnya Perda Nomor 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran.
Lilis Lisdawati, seorang perempuan yang menjadi korban salah tangkap razia pekerja seks komersial (PSK) meninggal dunia pada 2008 dalam kondisi depresi berat. Lilis, saat itu keluar di malam hari. Lilis yang keluar seorang diri mengenakan celana panjang dan jaket justru diciduk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena dianggap sedang menjajakan diri.
Padahal, kala itu, Lilis sedang menunggu angkutan umum. Akibat kejadian itu, Lilis harus meringkuk di balik jeruji dan Pemerintah Kota Tangerang membuka secara umum sidang perkaranya di pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, Lilis dan suaminya harus keluar dari tempat kerjanya dan berpindah tempat tinggal karena mendapat stigma buruk dari masyarakat.
Cerita lainnya, sejak 2008 jemaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat yang harus hidup tanpa akses pendidikan dan tak diperbolehkan berdagang hanya karena dinilai menodai nilai agama Islam. Padahal, Ahmadiyah telah ada 1930 dan berbadan hukum sejak 1950. Akibatnya, penyerangan yang terjadi menggusur jemaah Ahmadiyah yang sejak lama menjadi pedagang dan menguasai pasar setempat.
Dia menilai saat masalah kemiskinan dan korupsi belum terurai, Pemerintah Daerah yang seharusnya bisa menjadi penyambung tangan Pemerintah Pusat ternyata belum dapat menunjukkan perannya. Perebutan kekuasaan atas nama identitas pun terjadi mulai dari daerah.
“Perebutannya justru di daerah. Politik identitas terjadi di tingkat daerah. Banyak kemunafikan. Hipokritas atas nama gender, agama atau suku. Perda pelacuran dan penggunaan jilbab dibuat. Padahal, korupsi tinggi sekali di Banten. Intoleransi berujung pada penyerangan kelompok minoritas dan korbannya perempuan dan anak,” katanya. [Antara/Bisnis]