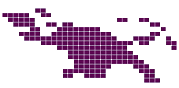Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nilai Pemerintah Indonesia Bungkam Kebebasan Pers di Tanah Papua
pada tanggal
Wednesday, 24 June 2015
JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno P. Marsudi, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko tentang kebebasan pers di Papua. Pernyataan ketiga pejabat ini, menurut AJI, hendak menutup-nutupi fakta pembungkaman kebebasan pers di Papua, lebih jauh pelanggaran hak asasi manusia di provinsi paling timur Indonesia itu.
Menurut ketiganya, tidak ada pembatasan akses jurnalis asing di Papua yang selama ini memunculkan keresahan. Selama ini, yang terjadi adalah mekanisme perizinan biasa yang justru membawa implikasi positif bagi Indonesia. Kepada jurnalis yang mewawancarainya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI, Senin (22 Juni 2015), Menlu Retno mengatakan, izin kepada jurnalis asing tetap diberikan, meskipun tidak semuanya. Pada 2012 misalnya, kata Retno, dari 11 permohonan liputan, 5 disetujui. Tahun 2013, dari 28 pengajuan, 21 disetujui dan pada tahun 2014, dari 27 permohonan liputan, sebanyak 22 disetujui. Bila toh ada penolakan, hal itu semata-mata karena hal administratif belaka, seperti alasan keamanan dan lainnya.
Senada, Kepala BIN Marciano Norman mengungkapkan, regulasi atas jurnalis asing ke Papua, justru memiliki semangat keberimbangan pada pemberitaan. Sekaligus sebagai upaya untuk menghindari upaya-upaya menyalahgunakan izin kunjungan ke Papua, yang justru merugikan Indonesia. Sementara Panglima TNI Jenderal Moeldoko, berkilah, pendampingan (baca: pengawasan) TNI atas jurnalis yang datang ke Papua, adalah upaya melindungi jurnalis.
AJI menyatakan, pernyataan ketiga pejabat ini nyata-nyata melawan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sudah menyatakan akan membuka akses pers asing seluas-luasnya di Papua. Ketiga bawahan Presiden ini tidak memahami bahwa kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara termasuk yang di Papua. Dan syarat mendasar bagi pemenuhan kedua hak asasi ini adalah kebebasan pers.
Pembatasan peliputan terutama oleh jurnalis asing di wilayah paling timur Indonesia ini sudah berlangsung sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia. Jurnalis-jurnalis asing yang akan meliput Papua harus melalui lembaga clearing house yang melibatkan 12 kementerian atau lembaga negara, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, sampai Kementerian Kooordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Mekanisme ini menjadi alat pemerintah membatasi jurnalis-jurnalis yang ingin melaporkan soal Papua secara bebas. Mekanisme clearing house ini tidak transparan karena memang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Alasan keberimbangan yang diutarakan Kepala BIN jelas adalah upaya menutup-nutupi praktik buruk selama puluhan tahun, sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Penutupan akses pers telah membuat informasi beredar tanpa terverifikasi karena terdapat media sosial dan Internet yang bisa membuat diseminasi informasi (yang tak terverifikasi) terjadi dalam sekian menit ke seluruh penjuru dunia.
Pembatasan pers termasuk pers asing hanya akan membuat informasi yang beredar dari Papua adalah informasi yang tak bisa diverifikasi, tak terkonfirmasi, namun karena ada pembatasan pers, informasi yang tak terverifikasi yang beredar melalui Internet tersebut justru menjadi konsumsi dunia internasional. Alih-alih, kebijakan tiga pejabat negara ini justru semakin menyudutkan Indonesia di dunia internasional. Pembatasan kebebasan pers di Papua jelas akan membuat jalan perdamaian di Papua semakin terjal.
Dalam catatan AJI, satu jurnalis Papua menjadi bagian dari delapan kasus kematian jurnalis yang tidak terselesaikan. Mereka adalah Fuad Muhammad Syafruddin (Bernas, Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat tewas 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003), Ersa Siregara (jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis tabloid Delta Pos, tewas 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).
Karena itulah, AJI menyatakan: 1). Mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno P. Marsudi, Kepala BIN Marciano Norman dan Panglima TNI Moedoko; 2). Menuntut pemerintah segera membubarkan lembaga clearing house dan membuka seluas-luasnya akses jurnalis di Papua; 3). Menuntut pemerintah melindungi jurnalis dari intimidasi aparat keamanan dan pihak-pihak lain, serta tidak melakukan tindakan memata-matai, meneror atau kegiatan-kegiatan lain yang menghambat kegiatan jurnalistik; dan 4). Mendesak pemerintah untuk memenuhi hak publik atas informasi sesuai UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. [AJI]
Menurut ketiganya, tidak ada pembatasan akses jurnalis asing di Papua yang selama ini memunculkan keresahan. Selama ini, yang terjadi adalah mekanisme perizinan biasa yang justru membawa implikasi positif bagi Indonesia. Kepada jurnalis yang mewawancarainya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI, Senin (22 Juni 2015), Menlu Retno mengatakan, izin kepada jurnalis asing tetap diberikan, meskipun tidak semuanya. Pada 2012 misalnya, kata Retno, dari 11 permohonan liputan, 5 disetujui. Tahun 2013, dari 28 pengajuan, 21 disetujui dan pada tahun 2014, dari 27 permohonan liputan, sebanyak 22 disetujui. Bila toh ada penolakan, hal itu semata-mata karena hal administratif belaka, seperti alasan keamanan dan lainnya.
Senada, Kepala BIN Marciano Norman mengungkapkan, regulasi atas jurnalis asing ke Papua, justru memiliki semangat keberimbangan pada pemberitaan. Sekaligus sebagai upaya untuk menghindari upaya-upaya menyalahgunakan izin kunjungan ke Papua, yang justru merugikan Indonesia. Sementara Panglima TNI Jenderal Moeldoko, berkilah, pendampingan (baca: pengawasan) TNI atas jurnalis yang datang ke Papua, adalah upaya melindungi jurnalis.
Baca Juga
AJI menyatakan, pernyataan ketiga pejabat ini nyata-nyata melawan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sudah menyatakan akan membuka akses pers asing seluas-luasnya di Papua. Ketiga bawahan Presiden ini tidak memahami bahwa kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara termasuk yang di Papua. Dan syarat mendasar bagi pemenuhan kedua hak asasi ini adalah kebebasan pers.
Pembatasan peliputan terutama oleh jurnalis asing di wilayah paling timur Indonesia ini sudah berlangsung sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia. Jurnalis-jurnalis asing yang akan meliput Papua harus melalui lembaga clearing house yang melibatkan 12 kementerian atau lembaga negara, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, sampai Kementerian Kooordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Mekanisme ini menjadi alat pemerintah membatasi jurnalis-jurnalis yang ingin melaporkan soal Papua secara bebas. Mekanisme clearing house ini tidak transparan karena memang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Alasan keberimbangan yang diutarakan Kepala BIN jelas adalah upaya menutup-nutupi praktik buruk selama puluhan tahun, sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Penutupan akses pers telah membuat informasi beredar tanpa terverifikasi karena terdapat media sosial dan Internet yang bisa membuat diseminasi informasi (yang tak terverifikasi) terjadi dalam sekian menit ke seluruh penjuru dunia.
Pembatasan pers termasuk pers asing hanya akan membuat informasi yang beredar dari Papua adalah informasi yang tak bisa diverifikasi, tak terkonfirmasi, namun karena ada pembatasan pers, informasi yang tak terverifikasi yang beredar melalui Internet tersebut justru menjadi konsumsi dunia internasional. Alih-alih, kebijakan tiga pejabat negara ini justru semakin menyudutkan Indonesia di dunia internasional. Pembatasan kebebasan pers di Papua jelas akan membuat jalan perdamaian di Papua semakin terjal.
Dalam catatan AJI, satu jurnalis Papua menjadi bagian dari delapan kasus kematian jurnalis yang tidak terselesaikan. Mereka adalah Fuad Muhammad Syafruddin (Bernas, Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat tewas 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003), Ersa Siregara (jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis tabloid Delta Pos, tewas 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).
Karena itulah, AJI menyatakan: 1). Mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno P. Marsudi, Kepala BIN Marciano Norman dan Panglima TNI Moedoko; 2). Menuntut pemerintah segera membubarkan lembaga clearing house dan membuka seluas-luasnya akses jurnalis di Papua; 3). Menuntut pemerintah melindungi jurnalis dari intimidasi aparat keamanan dan pihak-pihak lain, serta tidak melakukan tindakan memata-matai, meneror atau kegiatan-kegiatan lain yang menghambat kegiatan jurnalistik; dan 4). Mendesak pemerintah untuk memenuhi hak publik atas informasi sesuai UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. [AJI]