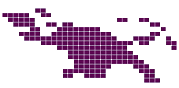Nasionalisasi Nasi, Ancam Rantai Kehidupan Orang Papua
pada tanggal
Thursday, 18 April 2013
YOGGIME (JAYAWIJAYA )- Pola makan orang Papua berubah seiring dengan kebijakan penyeragaman bahan makanan pokok secara nasional.
Dalam strata kehidupan masyarakat Papua, ubi, babi dan manusia berada dalam posisi setara. Rantai atau piramida kehidupan orang Papua yang terbangun sejak zaman nenek moyang itu kini terancam.
Sejumlah pria sedang menyiapkan tradisi bakar batu. Mereka adalah warga Kampung Yonggime, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kampung yang terletak di Lembah Baliem ini bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan hampir tiga jam dari Kota Wamena.
Awal Maret lalu tampaknya adalah hari yang istimewa bagi warga Kampung Yonggime. Ubi jalar yang mereka tanam sejak sembilan bulan lalu telah menghasilkan. Itu alasan mengapa mereka menggelar tradisi bakar batu, sebuah ritual adat yang sejak dahulu kala biasa digelar orang Papua, terutama yang tinggal di wilayah pegunungan.
Bagi orang asli Papua, tradisi memasak dengan cara tradisional ini umumnya digelar untuk menyambut suatu acara khusus atau istimewa. Setiap orang dalam tradisi itu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Kaum pria bertugas menyediakan batu untuk perapian dan menyiapkan lubang besar untuk dijadikan tempat memasak. Kaum perempuan menyiapkan ubi dan anak-anak mencari kayu bakar, rumput dan dedaunan. Dalam tradisi bakar batu, biasanya yang dimasak adalah ubi jalar dan babi. Babi atau dalam bahasa setempat wam ikut dimasak untuk menambah rasa asin dalam ubi jalar. Namun, siang itu, warga Kampung Yonggime hanya memasak ubi jalar.
Ubi jalar atau dalam bahasa setempat hipere adalah makanan asli pokok orang Papua. Sejak dahulu, nenek moyang orang Papua yang tinggal di wilayah pegunungan telah menggantungkan hidupnya dari ubi jalar yang hanya cocok ditanam di wilayah dataran tinggi.
Seorang antropolog berkebangsaan Amerika Serikat, Karl G Heider, pernah melakukan penelitian langsung mengenai ketergantungan orang Papua terhadap ubi jalar. Selain babi, buah dan sayur yang ditanam dan pelihara, Karl mengatakan, orang Papua menggantungkan hidupnya pada ubi jalar.
Pada 1963, Karl memulai penelitiannya dan tinggal bertahun-tahun untuk meneliti ubi jalar dan honai, rumah tradisional suku-suku di Lembah Baliem. Hasil penelitiannya tertuang dalam dua buku berjudul Dani Sweet Potatoes dan Dani Houses yang diterbitkan pada 1974.
Sumber Kehidupan
Kiloner Wenda, seorang penulis buku berjudul Ubi Jalar, Si Manis Pemberi Kehidupan mengatakan, ubi jalar telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan, antara lain dari budaya, adat dan sosial masyarakat Papua. Tidak hanya itu, Kiloner mengatakan, ubi jalar juga telah menjadi penopang ekonomi masyarakat pegunungan Papua.
Saat ini, Kiloner mengatakan, terdapat lebih kurang 250 jenis ubi jalar. Sebagian besar dari jumlah itu, Kiloner melanjutkan, telah dibudidayakan di Papua dan menjadi varietas unggulan. Ia aktif dalam aktivitas tersebut dan kini bekerja sebagai staf program pembudidayaan ubi jalar dari lembaga nirlaba internasional yang bermarkas di Inggris, Oxfam.
Hal senada disampaikan Selius Wenda dari Yayasan Pendidikan Usaha Mandiri (Yapum), sebuah organisasi lokal yang terlibat memberdayakan petani ubi jalar. Bagi orang Papua, Selius mengatakan, ubi mengandung nilai budaya dan sejarah. “Ubi jalar adalah makanan yang dimakan nenek moyang kita, orang Papua,” ujarnya.
Yapum adalah organisasi lokal yang digendeng Oxfam untuk memberdayakan petani ubi jalar di Papua. Tidak hanya itu, Yapum membeli ubi jalar dari petani sehingga mereka tidak perlu lagi menjualnya langsung ke pasar. Saat ini, Yapum menjalin kerja sama dengan 226 kelompok tani yang dengan jumlah anggota sekitar 5.600 orang di Kabupaten Jayawijaya.
Tidak hanya dalam tradisi bakar batu, kaum laki-laki dan perempuan yang tinggal di pegunungan juga memiliki peran berbeda dalam mengelola sumber makanan mereka, terutama dalam menanam ubi jalar. Demikian Adriana Wenda, seorang ibu dari Kampung Yonggime.
Adriana mengatakan, kaum pria memiliki tanggung jawab membuka lahan pertanian untuk ditanami ubi jalar. Kaum perempuan, kata Adriana, bertugas menggarap lahan seperti menanam, menyiram, membersihkan hingga memanen ubi jalar untuk dibawa ke rumah dan dijual.
“Satu noken kita bisa bawa pulang 150 (ubi). Itu untuk (makan) satu setengah hari. Lalu, itu kita kasih makan babi, baru keluarga di rumah. Saya pu anak ada lima. (Ubi) Yang bagus untuk kasih kita makan, yang tidak bagus kasih babi. Biasanya yang (ukurannya) kecil-kecil,” ujar Adriana.
Setiap hari, kata Adriana, kaum perempuan berada di kebun mulai pukul delapan pagi hingga tiga sore. Tidak hanya bertanggung jawab mengelola kebun, Adriana menambahkan, kaum perempuan saat ini juga bertugas menjual ubi jalar dari hasil panen ke pasar.
Selius menjelaskan, setiap keluarga petani biasanya tidak langsung mengambil sekaligus ubi jalar di lahannya. “Dia tidak gali satu kali langsung habis. Diperhitungkan untuk makan sehari saja. Diambil hari ini untuk makan pagi hingga sore, kemudian besoknya ke ladang lagi untuk ambil ubi,” kata Selius.
Ancaman Kehidupan
Namun, saat ini Papua menghadapi persoalan besar selain persoalan politik yang telah menimbulkan kegelisahan. Masyarakat Papua kini merasakan kegetiran menghadapi persoalan pangan. Warga kota-kota besar kerap mendengar berita kelaparan yang mewabah di banyak tempat di Papua dari media massa.
Itu terjadi akibat berubahnya pola makan dan menanam dari masyarakat Papua. Pada era 1980-an, Presiden Soeharto menyatakan bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Salah satu kebijakan itu adalah menjadikan Merauke sebagai lumbung padi melalui proyek besar, The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).
Kebijakan Soeharto menebar benih padi ke wilayah-wilayah di luar Jawa dijalankan seiring dengan berjalannya kebijakan transmigrasi yang memindahkan warga Pulau Jawa ke pulau-pulau lain. Kebijakan itu terus berlangsung hingga kini pemerintahan saat ini. Akibat kebijakan itu, muncul ketimpangan besar antara produksi dan konsumsi.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua mencatat, produksi ubi jalar dari tahun ke tahun terus merosot. Berdasarkan data periode 1997-2001, ubi jalar yang dihasilkan sekitar 576,309 ton per tahun. Namun, pada 2005 produksi ubi jalar merosot menjadi 273,871 ton dan 332,331 ton pada 2012.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga mencatat kebutuhan ubi jalar di Papua meningkat dari tahun ke tahun. Periode 1997-2001, kebutuhan untuk konsumsi ubi jalar 174,106 ton per tahun. Tahun 2005, konsumsi ubi jalar mencapai 190,531 ton dan terus meningkat hingga 322,421 ton ubi jalar pada 2012.
Selius mengatakan, pemerintah pusat dan daerah semestinya menyadari betapa pentingnya ubi jalar dalam kehidupan masyarakat Papua. Secara adat, kata dia, ubi dan babi berada dalam tingkat yang setara. Namun, bila dilihat dari struktur sosial, lanjutnya, “Ubi itu nomor satu, babi kemudian manusia.”
Ia kemudian memberikan gambaran sederhana, “Karena ada ubi, manusia bisa hidup. Karena ada ubi, babi bisa besar.” Namun, apa yang terjadi jika keberadaan ubi jalar kian terancam? Rantai atau piramida kehidupan manusia Papua pun terancam hilang. [SinarHarapan]
Dalam strata kehidupan masyarakat Papua, ubi, babi dan manusia berada dalam posisi setara. Rantai atau piramida kehidupan orang Papua yang terbangun sejak zaman nenek moyang itu kini terancam.
Sejumlah pria sedang menyiapkan tradisi bakar batu. Mereka adalah warga Kampung Yonggime, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kampung yang terletak di Lembah Baliem ini bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan hampir tiga jam dari Kota Wamena.
Baca Juga
Awal Maret lalu tampaknya adalah hari yang istimewa bagi warga Kampung Yonggime. Ubi jalar yang mereka tanam sejak sembilan bulan lalu telah menghasilkan. Itu alasan mengapa mereka menggelar tradisi bakar batu, sebuah ritual adat yang sejak dahulu kala biasa digelar orang Papua, terutama yang tinggal di wilayah pegunungan.
Bagi orang asli Papua, tradisi memasak dengan cara tradisional ini umumnya digelar untuk menyambut suatu acara khusus atau istimewa. Setiap orang dalam tradisi itu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Kaum pria bertugas menyediakan batu untuk perapian dan menyiapkan lubang besar untuk dijadikan tempat memasak. Kaum perempuan menyiapkan ubi dan anak-anak mencari kayu bakar, rumput dan dedaunan. Dalam tradisi bakar batu, biasanya yang dimasak adalah ubi jalar dan babi. Babi atau dalam bahasa setempat wam ikut dimasak untuk menambah rasa asin dalam ubi jalar. Namun, siang itu, warga Kampung Yonggime hanya memasak ubi jalar.
Ubi jalar atau dalam bahasa setempat hipere adalah makanan asli pokok orang Papua. Sejak dahulu, nenek moyang orang Papua yang tinggal di wilayah pegunungan telah menggantungkan hidupnya dari ubi jalar yang hanya cocok ditanam di wilayah dataran tinggi.
Seorang antropolog berkebangsaan Amerika Serikat, Karl G Heider, pernah melakukan penelitian langsung mengenai ketergantungan orang Papua terhadap ubi jalar. Selain babi, buah dan sayur yang ditanam dan pelihara, Karl mengatakan, orang Papua menggantungkan hidupnya pada ubi jalar.
Pada 1963, Karl memulai penelitiannya dan tinggal bertahun-tahun untuk meneliti ubi jalar dan honai, rumah tradisional suku-suku di Lembah Baliem. Hasil penelitiannya tertuang dalam dua buku berjudul Dani Sweet Potatoes dan Dani Houses yang diterbitkan pada 1974.
Sumber Kehidupan
Kiloner Wenda, seorang penulis buku berjudul Ubi Jalar, Si Manis Pemberi Kehidupan mengatakan, ubi jalar telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan, antara lain dari budaya, adat dan sosial masyarakat Papua. Tidak hanya itu, Kiloner mengatakan, ubi jalar juga telah menjadi penopang ekonomi masyarakat pegunungan Papua.
Saat ini, Kiloner mengatakan, terdapat lebih kurang 250 jenis ubi jalar. Sebagian besar dari jumlah itu, Kiloner melanjutkan, telah dibudidayakan di Papua dan menjadi varietas unggulan. Ia aktif dalam aktivitas tersebut dan kini bekerja sebagai staf program pembudidayaan ubi jalar dari lembaga nirlaba internasional yang bermarkas di Inggris, Oxfam.
Hal senada disampaikan Selius Wenda dari Yayasan Pendidikan Usaha Mandiri (Yapum), sebuah organisasi lokal yang terlibat memberdayakan petani ubi jalar. Bagi orang Papua, Selius mengatakan, ubi mengandung nilai budaya dan sejarah. “Ubi jalar adalah makanan yang dimakan nenek moyang kita, orang Papua,” ujarnya.
Yapum adalah organisasi lokal yang digendeng Oxfam untuk memberdayakan petani ubi jalar di Papua. Tidak hanya itu, Yapum membeli ubi jalar dari petani sehingga mereka tidak perlu lagi menjualnya langsung ke pasar. Saat ini, Yapum menjalin kerja sama dengan 226 kelompok tani yang dengan jumlah anggota sekitar 5.600 orang di Kabupaten Jayawijaya.
Tidak hanya dalam tradisi bakar batu, kaum laki-laki dan perempuan yang tinggal di pegunungan juga memiliki peran berbeda dalam mengelola sumber makanan mereka, terutama dalam menanam ubi jalar. Demikian Adriana Wenda, seorang ibu dari Kampung Yonggime.
Adriana mengatakan, kaum pria memiliki tanggung jawab membuka lahan pertanian untuk ditanami ubi jalar. Kaum perempuan, kata Adriana, bertugas menggarap lahan seperti menanam, menyiram, membersihkan hingga memanen ubi jalar untuk dibawa ke rumah dan dijual.
“Satu noken kita bisa bawa pulang 150 (ubi). Itu untuk (makan) satu setengah hari. Lalu, itu kita kasih makan babi, baru keluarga di rumah. Saya pu anak ada lima. (Ubi) Yang bagus untuk kasih kita makan, yang tidak bagus kasih babi. Biasanya yang (ukurannya) kecil-kecil,” ujar Adriana.
Setiap hari, kata Adriana, kaum perempuan berada di kebun mulai pukul delapan pagi hingga tiga sore. Tidak hanya bertanggung jawab mengelola kebun, Adriana menambahkan, kaum perempuan saat ini juga bertugas menjual ubi jalar dari hasil panen ke pasar.
Selius menjelaskan, setiap keluarga petani biasanya tidak langsung mengambil sekaligus ubi jalar di lahannya. “Dia tidak gali satu kali langsung habis. Diperhitungkan untuk makan sehari saja. Diambil hari ini untuk makan pagi hingga sore, kemudian besoknya ke ladang lagi untuk ambil ubi,” kata Selius.
Ancaman Kehidupan
Namun, saat ini Papua menghadapi persoalan besar selain persoalan politik yang telah menimbulkan kegelisahan. Masyarakat Papua kini merasakan kegetiran menghadapi persoalan pangan. Warga kota-kota besar kerap mendengar berita kelaparan yang mewabah di banyak tempat di Papua dari media massa.
Itu terjadi akibat berubahnya pola makan dan menanam dari masyarakat Papua. Pada era 1980-an, Presiden Soeharto menyatakan bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Salah satu kebijakan itu adalah menjadikan Merauke sebagai lumbung padi melalui proyek besar, The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).
Kebijakan Soeharto menebar benih padi ke wilayah-wilayah di luar Jawa dijalankan seiring dengan berjalannya kebijakan transmigrasi yang memindahkan warga Pulau Jawa ke pulau-pulau lain. Kebijakan itu terus berlangsung hingga kini pemerintahan saat ini. Akibat kebijakan itu, muncul ketimpangan besar antara produksi dan konsumsi.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua mencatat, produksi ubi jalar dari tahun ke tahun terus merosot. Berdasarkan data periode 1997-2001, ubi jalar yang dihasilkan sekitar 576,309 ton per tahun. Namun, pada 2005 produksi ubi jalar merosot menjadi 273,871 ton dan 332,331 ton pada 2012.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga mencatat kebutuhan ubi jalar di Papua meningkat dari tahun ke tahun. Periode 1997-2001, kebutuhan untuk konsumsi ubi jalar 174,106 ton per tahun. Tahun 2005, konsumsi ubi jalar mencapai 190,531 ton dan terus meningkat hingga 322,421 ton ubi jalar pada 2012.
Selius mengatakan, pemerintah pusat dan daerah semestinya menyadari betapa pentingnya ubi jalar dalam kehidupan masyarakat Papua. Secara adat, kata dia, ubi dan babi berada dalam tingkat yang setara. Namun, bila dilihat dari struktur sosial, lanjutnya, “Ubi itu nomor satu, babi kemudian manusia.”
Ia kemudian memberikan gambaran sederhana, “Karena ada ubi, manusia bisa hidup. Karena ada ubi, babi bisa besar.” Namun, apa yang terjadi jika keberadaan ubi jalar kian terancam? Rantai atau piramida kehidupan manusia Papua pun terancam hilang. [SinarHarapan]